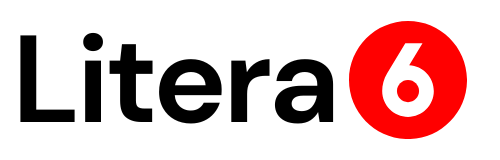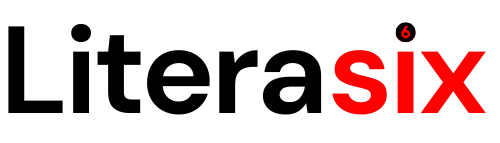Ketika orang berbicara tentang kemajuan, dua kata yang paling sering muncul adalah sains dan teknologi. Kedengarannya serupa, sering dipasangkan dalam pidato pejabat atau brosur universitas, bahkan terkadang diperlakukan seperti sinonim.
Padahal keduanya berbeda: sains adalah mesin pencari kebenaran, sementara teknologi adalah seni menerjemahkan kebenaran itu menjadi alat yang bisa dipakai manusia.
Namun, dalam era kecerdasan buatan, krisis iklim, dan perang digital hari ini, muncul pertanyaan menggoda: mana yang lebih penting untuk masa depan—sains atau teknologi?
Sains: Hasrat Murni untuk Memahami Dunia
Sains lahir dari rasa penasaran yang nyaris kekanak-kanakan. Galileo, misalnya, tidak puas hanya menatap bintang, ia ingin tahu bagaimana bintang-bintang itu bergerak. Newton bertanya mengapa apel jatuh, bukan melayang. Dari pertanyaan kecil ini, lahirlah teori besar yang mengubah peradaban.
Fungsi utama sains bukan menghasilkan produk, tetapi menghasilkan pengetahuan. Ilmuwan tidak selalu berpikir soal aplikasi praktis; mereka ingin memahami hukum dasar alam. Penemuan medan elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell di abad ke-19 misalnya, awalnya hanyalah abstraksi matematis. Namun, teori itu kemudian menjadi pondasi bagi radio, televisi, internet, hingga smartphone yang kini menempel di tangan kita 24 jam sehari.
Albert Einstein pernah berkata, “Ilmu tanpa agama pincang, agama tanpa ilmu buta.” Kutipan ini sering diperdebatkan, tetapi maksudnya jelas: sains adalah upaya manusia memahami realitas, dan pemahaman ini tidak boleh berdiri sendiri tanpa kerangka moral.
Sains, dengan demikian, adalah pencarian kebenaran, bukan pencarian keuntungan.
Teknologi: Dari Pengetahuan Menjadi Alat
Jika sains bertanya “mengapa?”, maka teknologi bertanya “bagaimana?”. Teknologi adalah cara manusia memanfaatkan pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis.
Pesawat terbang tidak mungkin ada tanpa pemahaman tentang aerodinamika. Vaksin tidak akan lahir tanpa pengetahuan mikrobiologi. Bahkan kecerdasan buatan yang kini meresahkan banyak orang adalah turunan dari riset matematika, linguistik, dan neurosains yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Steve Jobs, pendiri Apple, pernah berkata: “Teknologi saja tidak cukup—teknologi yang dipadukan dengan liberal arts, dengan humaniora, adalah yang memberikan hasil yang membuat hati bernyanyi.” Kalimat ini menegaskan bahwa teknologi bukan hanya alat mekanis, tetapi produk yang lahir dari gabungan ilmu pengetahuan, seni, dan imajinasi manusia.
Jika sains adalah otak, maka teknologi adalah tangan yang mewujudkan ide.
Hubungan Simbiotik: Otak dan Tangan Peradaban
Membandingkan sains dan teknologi seringkali tidak adil, karena keduanya seperti dua sisi mata uang. Tanpa sains, teknologi kehilangan pondasi. Tanpa teknologi, sains terkurung di jurnal akademik yang hanya dibaca segelintir orang.
Ambil contoh antibiotik. Penemuan Alexander Fleming terhadap jamur Penicillium pada 1928 adalah sains murni. Namun baru setelah teknologi farmasi berkembang, penicillin bisa diproduksi massal dan menyelamatkan jutaan nyawa.
Contoh lain: krisis iklim. Para ilmuwan iklim dengan sainsnya memprediksi naiknya suhu bumi, mencatat melelehnya es kutub, dan menghitung emisi karbon. Tetapi tanpa teknologi energi terbarukan—panel surya, turbin angin, kendaraan listrik—pengetahuan itu hanya akan menjadi alarm tanpa solusi.
Sains memberi peta, teknologi memberi kendaraan.
Masa Depan: Pertarungan Sains vs Teknologi?
Lalu, mana yang lebih penting untuk masa depan?
Jika kita bicara tentang survival, sains tampaknya vital. Ia memprediksi bencana, memahami penyakit baru, dan menemukan hukum dasar alam. Tanpa sains, manusia akan berjalan dalam kegelapan, hanya menebak-nebak.
Namun jika bicara tentang kehidupan sehari-hari, teknologi jelas dominan. Dunia kita hari ini lebih ditentukan oleh kehadiran teknologi—dari smartphone, media sosial, hingga artificial intelligence (AI). Kehidupan politik pun dipengaruhi algoritma. Bahkan pilihan belanja harian ditentukan oleh mesin rekomendasi.
Tetapi di sinilah jebakannya: ketika teknologi bergerak lebih cepat daripada sains, dunia bisa masuk ke wilayah berbahaya. AI misalnya, berkembang begitu cepat dalam aplikasi, sementara fondasi ilmiahnya—tentang kesadaran, etika, dan dampak sosial—masih kabur.
Yuval Noah Harari, sejarawan asal Israel, pernah mengingatkan: “Pertanyaan besar abad ini bukan apakah mesin bisa berpikir, tetapi apakah manusia masih bisa berpikir.” Sebuah sindiran halus bahwa teknologi yang tanpa kendali sains dan filsafat bisa menggeser manusia dari posisinya sendiri.
Sains di Negara Berkembang, Teknologi di Negara Maju
Ada pula dimensi geopolitik dalam perdebatan ini. Di negara maju, investasi pada sains dasar begitu besar. Amerika Serikat punya NASA, Eropa punya CERN, Jepang punya RIKEN. Sementara di banyak negara berkembang, teknologi lebih sering diimpor ketimbang diciptakan.
Indonesia, misalnya, lebih sering menjadi konsumen teknologi ketimbang produsen. Smartphone, kendaraan listrik, hingga mesin industri kebanyakan datang dari luar negeri. Tanpa investasi pada riset ilmiah, negara berkembang akan terus tergantung.
Ini membuktikan bahwa masa depan bangsa tidak bisa ditopang teknologi semata; ia butuh fondasi sains yang kuat.
Etika: Pertanyaan yang Tak Bisa Dijawab Teknologi
Pertanyaan penting lainnya: apakah semua pengetahuan harus diterjemahkan menjadi teknologi?
Kloning manusia, misalnya, secara ilmiah sudah mungkin. Tetapi apakah secara etis bisa diterima? Teknologi nuklir bisa menghasilkan listrik murah, tetapi juga bisa menghancurkan satu kota dalam sekejap. AI bisa membantu pekerjaan, tetapi juga berpotensi menghilangkan jutaan lapangan kerja.
Inilah mengapa kita tidak hanya butuh sains dan teknologi, tetapi juga filsafat. Tanpa filsafat, manusia bisa kehilangan arah dalam menggunakan kekuatan yang ia miliki.
Penutup: Keseimbangan, Bukan Pertarungan
Jadi, alih-alih bertanya mana yang lebih penting, mungkin yang lebih relevan adalah: bagaimana kita menyeimbangkan sains dan teknologi untuk masa depan?
Sains memberi kita pengetahuan, teknologi memberi kita kekuatan. Tetapi arah perjalanan tetap ditentukan oleh manusia itu sendiri.
Apakah pengetahuan dan kekuatan itu akan dipakai untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim, atau justru mempercepat kerusakannya? Apakah ia akan dipakai untuk memperpanjang usia manusia, atau menciptakan mesin yang membuat manusia tidak lagi relevan?
Masa depan tidak bergantung pada pertarungan sains melawan teknologi. Ia bergantung pada bagaimana kita, sebagai manusia, memilih menggunakan keduanya.