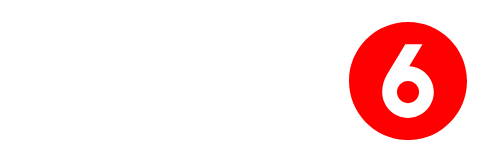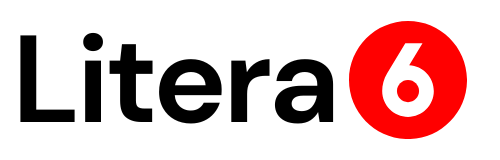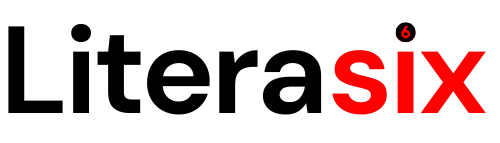Beberapa tahun terakhir, istilah self healing mendadak naik kelas. Dari status motivasi di Instagram, caption aesthetic di TikTok, hingga jargon para influencer yang hobi menjual buku catatan penuh kutipan penyemangat. Katanya, jalan-jalan ke pantai adalah self healing, minum kopi di kafe estetik pun disebut self healing.
Tapi di balik tren ini, muncul pertanyaan serius: benarkah self healing punya dasar ilmiah dalam psikologi, atau sekadar mitos modern yang dipoles media sosial?
Apa Itu Self Healing?
Secara sederhana, self healing berarti proses menyembuhkan diri sendiri, terutama dari luka batin atau tekanan psikologis. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam tradisi psikologi, gagasan bahwa manusia bisa pulih dengan bantuan mekanisme internal sudah lama dibahas.
Carl Rogers, tokoh psikologi humanistik, percaya bahwa setiap individu memiliki “tendensi aktualisasi” — dorongan alami untuk tumbuh dan menyembuhkan diri. Dalam pandangan ini, manusia bukan sekadar objek penderita masalah mental, melainkan subjek yang mampu berproses menuju kesehatan.
Namun, yang dimaksud Rogers jelas berbeda dengan self healing ala Instagram. Ia berbicara tentang refleksi, terapi berbasis empati, dan perjalanan panjang mengenali diri. Bukan sekadar menghirup kopi latte lalu mengaku sembuh.
Self Healing dalam Psikologi Modern
Psikologi kontemporer mengenal konsep coping mechanism dan resilience — cara individu menghadapi stres dan bangkit kembali dari trauma. Self healing, dalam kerangka ilmiah, terkait dengan:
Mindfulness: kesadaran penuh terhadap diri dan lingkungan saat ini, terbukti membantu mengurangi kecemasan.
Journaling: menulis pengalaman dan emosi untuk memahami pola pikir.
Self-compassion: memberi belas kasih pada diri sendiri alih-alih terus menyalahkan diri.
Meditasi & relaksasi: metode yang terbukti secara klinis menurunkan kadar stres.
Artinya, self healing bukan sekadar jargon; ada metode psikologi yang mendukungnya. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada sejauh mana individu benar-benar menjalani proses itu, bukan sekadar mengklaimnya di media sosial.
Ketika Self Healing Jadi Mitos Populer
Fenomena media sosial mengubah self healing menjadi kata sakti. Apa pun bisa ditempel label ini: traveling, shopping, skincare, bahkan rebahan seharian. Masalahnya, ketika semua hal dianggap self healing, maknanya jadi kabur.
Psikolog dari University of Pennsylvania, Martin Seligman, pernah menekankan pentingnya positive psychology — fokus pada kekuatan, bukan hanya kelemahan. Namun, konsep ini lalu sering disalahpahami sebagai “asal happy sudah cukup untuk sembuh.” Padahal, tidak sesederhana itu.
Bahaya mitos self healing populer adalah:
Mengabaikan masalah serius. Depresi klinis tidak bisa sembuh hanya dengan jalan-jalan ke Bali.
Menciptakan ilusi instan. Banyak orang kecewa karena “sudah self healing tapi kok masih stres?”
Komodifikasi luka. Industri wellness menjual self healing sebagai produk: dari paket retreat jutaan rupiah hingga buku catatan kosong yang dipasarkan sebagai “healing journal.”
Studi Kasus: Pandemi dan Self Healing
Saat pandemi Covid-19, istilah self healing makin populer. Banyak orang terkurung di rumah, mengalami stres, kecemasan, bahkan trauma kehilangan orang tercinta. Dalam situasi ini, praktik sederhana seperti meditasi, olahraga ringan, atau menulis jurnal memang membantu banyak orang menjaga kewarasan.
Namun di sisi lain, meningkat pula kasus depresi berat yang butuh intervensi profesional. Data WHO menunjukkan bahwa gangguan kecemasan dan depresi global meningkat 25% pada tahun pertama pandemi. Fakta ini menunjukkan bahwa self healing tidak bisa menjadi satu-satunya solusi.
Psikologi Klinis vs Self Healing Mandiri
Dalam psikologi klinis, penyembuhan luka mental seringkali membutuhkan bantuan eksternal: konseling, terapi kognitif-perilaku, hingga pengobatan medis. Self healing bisa menjadi bagian dari proses itu, tetapi bukan pengganti.
American Psychological Association (APA) menekankan pentingnya dukungan sosial dan terapi profesional bagi penderita depresi atau PTSD. Artinya, mengandalkan self healing saja sama dengan mencoba mengoperasi diri sendiri tanpa dokter—berbahaya dan berisiko.
Jadi, Manjur atau Mitos?
Jawabannya: dua-duanya.
Self healing manjur jika dipahami sebagai usaha sadar untuk merawat diri—melalui refleksi, mindfulness, journaling, dan kebiasaan sehat. Ia menjadi mitos jika direduksi menjadi aktivitas konsumtif atau klaim instan di media sosial.
Seperti halnya obat, dosis menentukan apakah ia menjadi penyembuh atau sekadar placebo.
Penutup: Antara Kopi Latte dan Keheningan Diri
Self healing tidak bisa diperlakukan sebagai tren musiman. Ia bukan sekadar jalan-jalan ke pantai atau membeli barang baru. Ia adalah proses panjang, penuh jatuh bangun, kadang membutuhkan bantuan profesional, kadang cukup dengan keberanian menatap diri sendiri.
Jadi, sebelum buru-buru menulis caption “lagi self healing” di Instagram, mungkin ada baiknya bertanya: apakah yang kita lakukan benar-benar menyembuhkan, atau hanya pelarian sesaat?