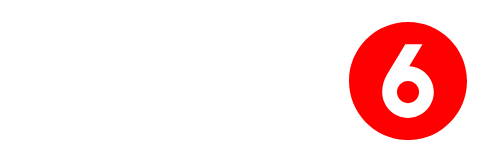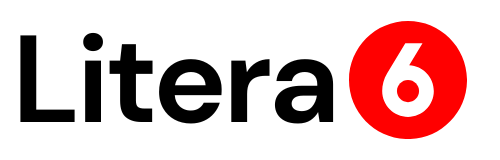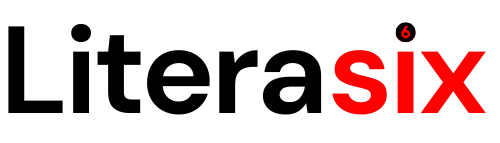Setiap Senin pagi, ribuan karyawan berangkat ke kantor dengan secangkir kopi dan sejumput doa bahwa minggu ini akan lebih bersahabat. Di dinding ruang kerja mereka, poster-poster berwarna pastel menampilkan kata-kata motivasi: “Work hard, play hard” atau “Balance is the key to happiness.”
Namun, dalam kenyataan, keseimbangan itu jarang benar-benar hadir. Work life balance, istilah yang kerap dijual sebagai penawar stres modern, perlahan berubah menjadi jargon pemasaran—baik di perusahaan maupun iklan multivitamin. Pertanyaannya: apakah work life balance benar-benar nyata, atau sekadar mitos yang kita konsumsi seperti pil vitamin C?
Sejarah Singkat Istilah Work Life Balance
Konsep work life balance pertama kali populer di Inggris pada akhir 1970-an dan berkembang di Amerika Serikat pada 1980-an. Awalnya, isu ini muncul sebagai reaksi atas jam kerja panjang akibat revolusi industri modern dan meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja.
Organisasi buruh dan pakar manajemen mengangkat gagasan ini sebagai upaya menyeimbangkan tanggung jawab profesional dengan kehidupan pribadi. Dalam teori, work life balance terdengar ideal: pekerjaan tak boleh menggerus ruang keluarga, hobi, atau kesehatan mental.
Tetapi sejak masuk ke dunia korporasi modern, istilah ini sering kali kehilangan makna. Ia menjadi slogan manajemen, dicetak di brosur perekrutan, dan akhirnya dipasarkan ulang dalam bentuk seminar motivasi hingga iklan vitamin penambah energi.
Realitas di Lapangan
Menurut laporan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Indonesia masuk dalam daftar negara dengan jam kerja paling panjang di dunia. Rata-rata pekerja Indonesia bekerja lebih dari 40 jam per minggu, melampaui banyak negara Eropa yang sudah menerapkan sistem kerja fleksibel.
Sementara itu, survei Microsoft 2022 Work Trend Index menunjukkan 47% pekerja global merasa kelelahan akibat tekanan kerja digital yang semakin intens, terutama sejak pandemi COVID-19 mendorong sistem kerja hybrid.
Ironisnya, meskipun perusahaan kerap menyuarakan well-being karyawan, praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya: target yang meningkat, rapat virtual tak berkesudahan, dan budaya “online selalu” yang membuat batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur.
Dari Korporasi ke Industri Kesehatan
Di sinilah iklan masuk mengambil peran. Jika kita perhatikan, banyak produk kesehatan seperti vitamin, minuman energi, hingga aplikasi meditasi digital menggunakan jargon work life balance dalam kampanye mereka.
-
Vitamin dipromosikan dengan narasi “agar tetap fit meski sibuk kerja.”
-
Minuman energi menjanjikan stamina untuk meeting marathon.
-
Aplikasi meditasi menawarkan ketenangan lima menit di sela pekerjaan.
Work life balance pun direduksi menjadi soal konsumsi produk. Seolah-olah keseimbangan hidup bisa dibeli lewat kapsul suplemen atau langganan aplikasi bulanan.
Padahal, akar masalahnya lebih struktural: jam kerja panjang, ekspektasi berlebihan dari atasan, hingga absennya regulasi yang menyeimbangkan kepentingan pekerja.
Perspektif Psikologi
Psikolog organisasi menyebut fenomena ini sebagai ilusi kendali. Kita merasa bisa mengatur keseimbangan kerja dan hidup dengan “tips praktis”: bangun lebih pagi, olahraga 15 menit, atau minum vitamin. Namun, dalam kenyataannya, kendali utama ada pada struktur pekerjaan itu sendiri.
Sebuah studi di Harvard Business Review menyebutkan bahwa pekerja yang benar-benar merasakan work life balance biasanya bukan karena manajemen waktu pribadi, melainkan karena perusahaan mereka menerapkan fleksibilitas kerja yang nyata—misalnya, cuti panjang, kebijakan remote, atau target yang realistis.
Dengan kata lain, work life balance bukanlah tanggung jawab individu semata. Ia memerlukan dukungan institusional. Tanpa itu, jargon ini hanya jadi mitos yang dikonsumsi pekerja seperti placebo.
Antara Lembur dan “Self-Care”
Di Indonesia, budaya kerja lembur masih menjadi norma. Bahkan, sebagian pekerja bangga menunjukkan loyalitas lewat jam kerja panjang. Fenomena ini diperkuat oleh istilah “kerja adalah ibadah” yang sering disalahartikan.
Akibatnya, banyak pekerja yang merasa bersalah jika pulang tepat waktu. Dalam ruang digital, istilah “healing” muncul sebagai pelarian. Orang-orang mengasosiasikan liburan singkat atau belanja online sebagai bentuk self-care. Namun, seperti iklan vitamin, healing sering kali tak menyentuh akar masalah: ketidakseimbangan struktural dalam dunia kerja.
Menuju Definisi Baru Work Life Balance
Jika work life balance versi lama sudah terkooptasi oleh jargon korporasi dan iklan, lalu apa definisi barunya?
-
Fleksibilitas, bukan jam kerja panjang.
Perusahaan perlu memberi ruang bagi pekerja untuk mengatur ritme kerja sendiri. -
Kesehatan mental setara dengan produktivitas.
Konseling, cuti kesehatan mental, dan sistem kerja manusiawi harus menjadi standar, bukan bonus. -
Kebijakan negara.
Regulasi ketenagakerjaan perlu menyesuaikan dengan tantangan zaman. Misalnya, pengawasan terhadap jam kerja digital yang sering kali tak terhitung sebagai lembur. -
Budaya sosial baru.
Masyarakat perlu berhenti memuja “sibuk” sebagai simbol sukses. Menghargai waktu luang sama pentingnya dengan menghargai prestasi kerja.
Dari Mitos ke Realitas
Work life balance, dalam bentuknya saat ini, sering kali hanyalah mitos. Ia hadir dalam brosur perekrutan, motivasi HR, hingga iklan vitamin yang menjanjikan energi instan. Namun, jika kita gali lebih dalam, keseimbangan hidup tidak bisa dibeli atau dicetak di poster dinding kantor.
Ia membutuhkan perubahan mendasar: dari budaya kerja, kebijakan perusahaan, hingga kesadaran masyarakat. Tanpa itu, istilah ini akan terus menjadi jargon manis—layaknya janji vitamin yang katanya bisa menyembuhkan kelelahan hidup, padahal hanya menunda rasa letih sebentar.