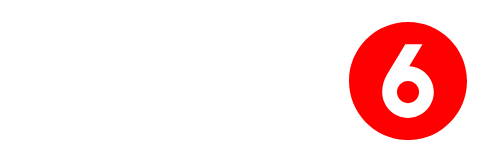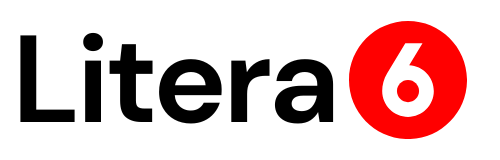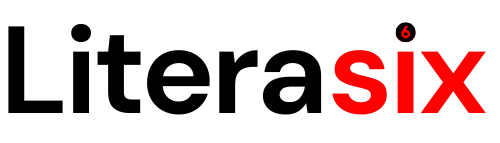Bayangkan pagi Anda: alarm ponsel berdering, jari otomatis membuka WhatsApp, notifikasi TikTok berseliweran, saldo e-wallet dicek sebelum membeli kopi. Semua itu terasa wajar, bahkan banal. Namun, setiap sentuhan layar meninggalkan jejak digital—entah berupa lokasi, preferensi, atau bahkan detak kebosanan yang terbaca dari durasi scroll.
Di balik rutinitas sederhana, ada industri raksasa yang bekerja tanpa tidur: kapitalisme digital, mesin yang menyulap data menjadi emas. Pertanyaannya, ketika kita sibuk mengonsumsi informasi, siapa sebenarnya yang sedang mengonsumsi kita?
Kapitalisme Data: Dari Komoditas ke Komodifikasi Manusia
Kapitalisme selalu menemukan objek baru untuk dieksploitasi. Dulu tanah dan tenaga kerja, lalu mesin dan modal finansial. Kini, abad ke-21 melahirkan komoditas baru yang lebih licin: data. Shoshana Zuboff dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism menyebut fenomena ini sebagai kapitalisme pengawasan: sebuah sistem di mana pengalaman pribadi kita diubah menjadi produk.
Google tidak hanya mesin pencari, ia adalah pengarsip niat manusia. Meta tidak sekadar media sosial, ia adalah pengelola relasi, pertemanan, bahkan percintaan. Amazon membaca pola konsumsi kita seperti cenayang modern, sementara TikTok adalah pabrik atensi yang meramu algoritma untuk memastikan mata kita terpaku lebih lama dari yang kita kira.
Ironisnya, kapitalisme digital bukan hanya menjual barang atau jasa. Ia menjual prediksi perilaku—seolah manusia hanyalah deretan probabilitas yang bisa dipetakan dan dimonetisasi.
Literasi Digital: Tameng atau Sekadar Slogan?
Di Indonesia, “literasi digital” telah menjadi mantra yang diulang dalam seminar kementerian, lomba sekolah, hingga iklan provider telekomunikasi. Isinya? Tips membedakan hoaks, menjaga etika berkomentar, dan cara mengaktifkan verifikasi dua langkah. Penting, tentu saja. Tapi masalahnya, literasi digital di sini berhenti di permukaan: do and don’t ala buku panduan, tanpa menyentuh struktur kekuasaan yang lebih dalam.
Kita diajari tidak membagikan berita palsu, tapi jarang diajari bertanya: mengapa berita palsu lebih cepat viral ketimbang klarifikasi? Kita diajari sopan di media sosial, tapi tidak pernah disadarkan bahwa setiap like, share, dan komentar adalah bahan bakar bagi mesin iklan yang menguntungkan segelintir konglomerat teknologi.
Sederhananya, literasi digital yang kita kenal hari ini lebih mirip kursus sopan santun online, bukan pendidikan kritis. Kita dibiarkan cerdas secara teknis, tapi tetap naif secara politis.
Siapa yang Mengendalikan?
Pertanyaan ini membawa kita ke jantung persoalan: siapa pemilik kendali atas data kita?
-
Google menguasai niat dan rasa penasaran, dengan 90% dominasi pasar mesin pencari.
-
Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) menguasai ruang interaksi sosial miliaran manusia.
-
Amazon tahu kebiasaan belanja Anda lebih baik dari pasangan Anda sendiri.
-
ByteDance lewat TikTok menguasai atensi anak muda global, dari Jakarta hingga New York.
Dan jangan lupa, negara ikut bermain. Tiongkok dengan Great Firewall-nya, Amerika dengan program pengawasan NSA, hingga wacana RUU data pribadi di Indonesia yang kadang terasa lebih sibuk melindungi kepentingan korporasi ketimbang warganya.
Dalam lanskap ini, rakyat biasa diminta “melek digital”—tapi pada saat yang sama tidak pernah diberi kendali penuh atas datanya sendiri. Seolah-olah literasi digital hanya versi halus dari nasihat lama: “jadi warga yang baik, jangan banyak tanya.”
Literasi Digital yang Sesungguhnya
Kalau begitu, apa arti literasi digital yang sejati? Ia bukan sekadar kemampuan memblokir nomor pinjaman online atau membedakan berita clickbait. Literasi digital yang sesungguhnya adalah kesadaran kritis:
-
Menyadari bahwa data bukan sekadar milik pribadi, tapi juga sumber kekuasaan ekonomi-politik.
-
Memahami bahwa setiap aplikasi gratis yang kita gunakan sebenarnya sudah dibayar mahal dengan privasi.
-
Mengakui bahwa kapitalisme digital bukan soal teknologi, tapi soal siapa yang punya kuasa atas masa depan demokrasi, konsumsi, bahkan identitas manusia.
Pada akhirnya, literasi digital tidak boleh berhenti pada keterampilan, tapi harus naik kelas menjadi gerakan politik warganet: berani menuntut regulasi adil, transparansi algoritma, dan hak kepemilikan data individu.
Penutup: Pengguna atau Bahan Baku?
Di tengah derasnya arus digital, kita sering merasa sebagai “pengguna teknologi”. Padahal, lebih tepatnya kita adalah bahan baku—diproses, diolah, dan dipasarkan oleh kapitalisme digital.
Maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi “apakah kita melek digital?”, melainkan: apakah kita siap merebut kendali atas data kita sendiri, atau selamanya menjadi komoditas dalam pabrik kapitalisme global?
Sampai saat itu tiba, setiap kali kita membuka ponsel, ingatlah satu hal: mungkin bukan kita yang sedang menggunakan teknologi, tapi teknologi—bersama kapitalisme di belakangnya—yang sedang menggunakan kita.