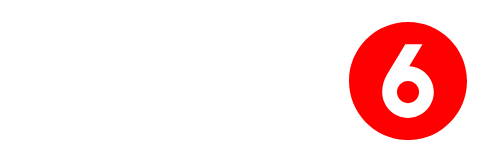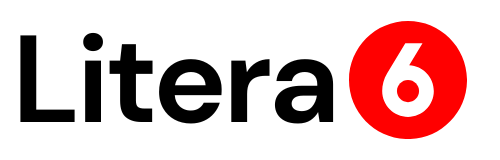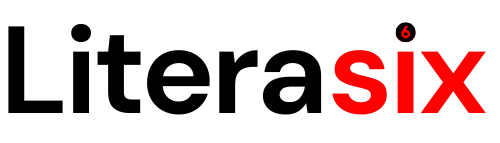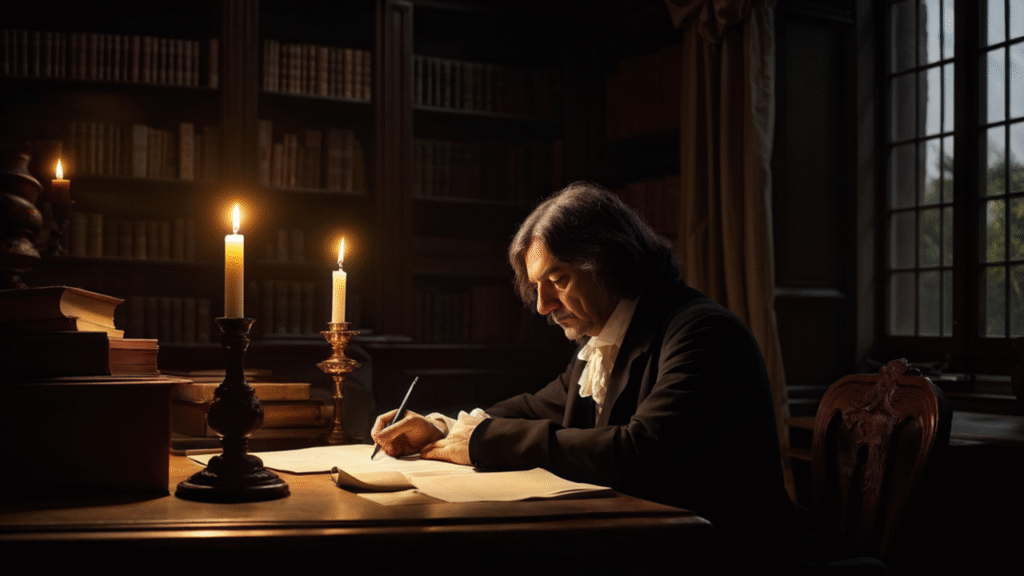Literasix — Eropa abad ke-17 adalah panggung besar yang dipenuhi kontradiksi: di satu sisi, gereja masih menggenggam kebenaran mutlak, namun di sisi lain, sains baru mulai berani menggeliat. Di tengah perang, wabah, dan perburuan bidat, lahirlah seorang pemikir yang tubuhnya ringkih namun pikirannya teguh: René Descartes. Ia bukan sekadar filsuf, melainkan seorang pemberontak intelektual yang berani menggugat fondasi pengetahuan. Jika abad pertengahan dibangun di atas otoritas tradisi dan wahyu, maka Descartes adalah arsitek zaman baru yang berani menempatkan manusia—dengan akalnya—sebagai pusat segalanya.
Dari ruang studinya yang sunyi hingga pengembaraannya di Eropa, Descartes melahirkan ide yang mengubah wajah filsafat: cogito, ergo sum — aku berpikir, maka aku ada. Kalimat sederhana ini bukan sekadar kutipan populer, melainkan tonggak kelahiran filsafat modern. Dengan metode keraguannya yang radikal, Descartes mengajarkan dunia bahwa kepastian sejati hanya bisa lahir setelah kita meragukan segalanya. Ia merobohkan bangunan dogma lama untuk membangun fondasi baru: rasio manusia sebagai pusat kebenaran.
1. Latar Sejarah dan Biografi Descartes
Untuk memahami René Descartes, kita harus menengok Eropa abad ke-17. Dunia sedang bergolak. Gereja Katolik masih memegang otoritas mutlak, tetapi benih pemberontakan intelektual mulai tumbuh. Reformasi Protestan baru saja mengguncang, Galileo dihukum karena mengusik pusat kosmos, dan perang tiga puluh tahun melanda Eropa, memporak-porandakan jutaan jiwa. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian inilah Descartes lahir pada tahun 1596 di La Haye en Touraine, Prancis.
Descartes lahir dari keluarga bangsawan kecil. Ayahnya seorang pengacara di parlemen Bretagne, ibunya meninggal ketika ia baru berusia satu tahun. Tubuhnya rapuh, sering sakit, sehingga ia terbiasa hidup dalam keheningan dan kontemplasi. Masa kecilnya dihabiskan di sekolah Jesuit La Flèche, salah satu institusi pendidikan paling bergengsi pada masa itu. Di sana ia diajarkan logika Aristoteles, teologi, dan filsafat skolastik.
Namun, alih-alih puas dengan dogma, Descartes justru gelisah. Ia merasa pengetahuan yang diajarkan tidak benar-benar memberikan kepastian. Seperti anak muda pada zamannya, ia juga mencoba karier militer. Ia bergabung dengan pasukan bayaran, berkeliling ke berbagai negara Eropa. Tetapi, kehidupan prajurit tidak membuatnya betah. Ia lebih sering mengasingkan diri, menulis catatan, dan merenung tentang dasar pengetahuan.
Pengembaraan intelektualnya akhirnya membawanya ke Belanda, di mana ia menetap selama lebih dari 20 tahun. Di negeri inilah ia menulis karya-karya besar seperti Discours de la méthode (1637) dan Meditationes de prima philosophia (1641). Pada tahun 1649, ia diundang ke Swedia oleh Ratu Christina yang tertarik pada filsafatnya. Ironisnya, udara dingin Stockholm justru mempercepat kematiannya. Descartes meninggal pada 1650, di usia 53 tahun.
Tetapi warisan intelektualnya jauh lebih panjang dari hidupnya sendiri. Dialah yang membuka pintu filsafat modern, dengan satu gagasan radikal: untuk membangun kepastian, kita harus mulai dari keraguan.
2. Metode Keraguan dan “Cogito Ergo Sum”
Gagasan paling terkenal dari Descartes terangkum dalam kalimat Latin: Cogito, ergo sum — Aku berpikir, maka aku ada. Kalimat ini sering dikutip, tetapi jarang dipahami kedalaman proses yang melahirkannya.
Bagi Descartes, masalah utama filsafat adalah bagaimana mendapatkan kepastian dalam pengetahuan. Ia melihat bahwa indra sering menipu. Mata bisa melihat fatamorgana, telinga bisa salah dengar, mimpi bisa terasa seperti kenyataan. Bagaimana kita bisa percaya pada sesuatu yang begitu rapuh?
Descartes lalu membayangkan kemungkinan paling ekstrem: bagaimana jika ada “iblis penipu” (evil demon) yang mengendalikan persepsi kita, membuat kita percaya pada hal-hal yang sebenarnya salah? Jika semua bisa ditipu, apa yang tersisa?
Jawaban Descartes: keraguan itu sendiri. Saat ia meragukan, ia tetap berpikir. Dan jika ia berpikir, ia pasti ada. Inilah titik kepastian mutlak pertama: kesadaran diri.
Dari cogito, Descartes membangun seluruh sistem filsafatnya. Ia menyusun argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan (sebagai jaminan bahwa dunia tidak sekadar ilusi), dan dari situ membangun sains yang kokoh. Tetapi lebih dari itu, ia meletakkan dasar bahwa subjek manusia adalah pusat pengetahuan. Bukan lagi dogma, bukan lagi otoritas eksternal, melainkan kesadaran individual.
Metode keraguan Descartes sebenarnya bukan tujuan akhir, melainkan sebuah jalan. Ia ingin menyingkirkan semua kepalsuan agar bisa menemukan dasar yang benar-benar kokoh. Keraguan bagi Descartes ibarat asam yang melarutkan segala hal rapuh, menyisakan hanya kebenaran yang tahan uji.
3. Descartes dan Ilmu Pengetahuan
Selain filsuf, Descartes adalah ilmuwan besar. Ia percaya bahwa dunia dapat dipahami dengan bahasa yang sama: matematika. Dalam Discours de la méthode, ia menulis empat aturan berpikir yang sangat mirip dengan metode ilmiah modern: jangan menerima apa pun tanpa bukti jelas, pecah persoalan menjadi bagian kecil, mulai dari hal sederhana, lalu buat sintesis menyeluruh.
Sumbangan paling konkret Descartes adalah penciptaan geometri analitik. Dengan memperkenalkan sistem koordinat (yang kini kita sebut Cartesian coordinate system), ia menjembatani aljabar dan geometri. Dari sinilah berkembang kalkulus Newton dan Leibniz, fisika modern, hingga grafik komputer hari ini.
Di bidang optik, ia menjelaskan hukum pembiasan cahaya. Dalam biologi, ia menggambarkan tubuh manusia sebagai mesin: jantung adalah pompa, darah mengalir seperti cairan mekanis, saraf seperti kabel. Pandangan ini disebut mekanistik-deterministik, yaitu gagasan bahwa tubuh dan alam semesta bekerja seperti jam raksasa yang tunduk pada hukum pasti.
Namun Descartes tidak berhenti pada materialisme murni. Ia tetap memisahkan dua substansi: res extensa (materi yang bisa diukur) dan res cogitans (pikiran yang tak bisa direduksi ke materi). Pandangan dualisme ini kemudian melahirkan perdebatan panjang: bagaimana pikiran yang non-materi bisa memengaruhi tubuh yang materi? Ia menunjuk kelenjar pineal sebagai titik pertemuan, tetapi banyak filsuf menganggap ini kelemahan besar dalam sistemnya.
Meskipun demikian, pandangan mekanistik Descartes memberi dasar kokoh bagi sains modern. Tanpa kerangka pikirannya, mungkin Newton tak akan menulis Principia, dan revolusi ilmiah takkan secepat itu.
4. Kritik, Kontroversi, dan Warisan
Tidak semua orang sependapat dengan Descartes. Kaum empiris seperti John Locke dan David Hume menolak klaim rasionalisme mutlak. Bagi mereka, pengetahuan bukan datang dari akal semata, melainkan dari pengalaman inderawi. Jika Descartes terlalu mengandalkan “cogito”, para empiris mengingatkan bahwa tanpa pengalaman, akal hanyalah mesin kosong.
Kritik lain datang dari masalah solipsisme. Jika satu-satunya kepastian adalah kesadaran diri, bagaimana kita membuktikan bahwa orang lain benar-benar ada? Apakah dunia luar bukan sekadar ilusi pikiran? Pertanyaan ini menghantui filsafat modern, hingga kemudian Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre mencoba keluar dari jebakan Cartesian dengan menekankan keberadaan-dalam-dunia (being-in-the-world).
Di sisi lain, warisan Descartes juga bercabang ke arah yang produktif. Filsuf besar seperti Spinoza dan Leibniz memulai sistem mereka dari inspirasi Cartesian. Kant, meski mengkritik, tetap membangun filsafat kritisnya di atas kerangka pertanyaan Descartes.
Lebih jauh lagi, sains modern — dari fisika Newton, biologi mekanistik, hingga psikologi kognitif — semua berdiri di atas fondasi Cartesian. Bahkan kritik paling keras terhadapnya justru membuktikan besarnya pengaruhnya.
5. Descartes di Era Modern
Apa relevansi Descartes di abad ke-21? Lebih banyak dari yang kita kira.
Pertama, dalam bidang teknologi. AI, big data, dan algoritma adalah anak kandung pemikiran Cartesian. Dengan memandang dunia sebagai data yang bisa dipetakan secara matematis, kita mewarisi visi Descartes bahwa alam semesta adalah sistem mekanis yang bisa dimodelkan. Tetapi sekaligus, problem mind-body tetap menghantui: apakah AI yang sangat canggih benar-benar bisa “berpikir”? Atau kesadaran tetap sesuatu yang tak bisa direduksi ke algoritma?
Kedua, dalam politik. Prinsip “cogito” bisa dimaknai sebagai dasar demokrasi modern: setiap individu memiliki rasio, dan karenanya memiliki hak untuk menentukan kebenaran sendiri. Tetapi di era post-truth, gagasan ini bisa berbalik. Jika setiap orang merasa benar hanya karena berpikir, bukankah itu membuka ruang bagi hoaks dan fanatisme opini?
Ketiga, dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah banjir informasi digital, keraguan Descartes justru lebih relevan dari sebelumnya. Kita perlu skeptis, bertanya ulang, meragukan data, bahkan meragukan diri sendiri. Metode keraguan bukan sekadar filosofi abad ke-17, melainkan bekal bertahan hidup di dunia modern.
Mungkin Descartes tidak akan mengenali dunia kita hari ini, tetapi ia pasti tersenyum melihat satu hal: bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan masih hidup, masih diperdebatkan, dan masih membentuk cara kita berpikir.
Penutup: Dari Keraguan Lahir Kepastian
René Descartes adalah paradoks. Ia seorang peragu, tetapi justru dari keraguan itulah lahir kepastian. Ia seorang rasionalis yang membela kepastian akal, tetapi membuka pintu bagi krisis epistemologi modern. Ia seorang ilmuwan mekanistik, tetapi tetap menyisakan ruang untuk jiwa.
Warisan terbesarnya bukanlah sistem yang sempurna, melainkan cara berpikir yang berani meragukan. Tanpa Descartes, filsafat mungkin masih terjebak dalam bayang-bayang skolastik. Tanpa Descartes, sains mungkin tidak tumbuh secepat itu. Tanpa Descartes, mungkin kita takkan berani mempertanyakan otoritas dan mencari dasar kebenaran dalam diri sendiri.
Pada akhirnya, Descartes mengingatkan kita: jangan takut meragukan. Karena di balik keraguan, ada kepastian yang lebih sejati. Dan dari kepastian itu, dunia baru bisa dibangun.