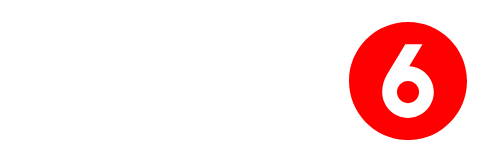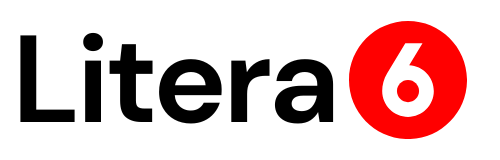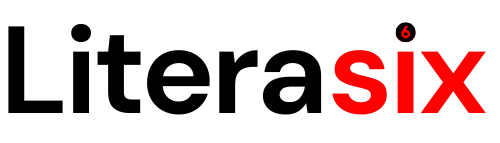Bayangkan seseorang sedang berjalan di trotoar pada siang hari. Cuaca cukup terik, kendaraan berseliweran, dan di sisi jalan beberapa orang nongkrong sambil berbincang. Tiba-tiba terdengar suara lantang: “Eh manis, senyumnya dong!” atau “Wih, cantik banget, mau kemana?” — suara yang sering disertai siulan, lirikan, atau tawa berlebihan.
Itulah yang disebut catcalling: pelecehan verbal di ruang publik, sering kali dilabeli sebagai “guyonan” atau “sekadar memuji,” padahal bagi banyak korban, hal itu adalah bentuk gangguan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan rasa takut.
Di Indonesia, fenomena ini kerap dipandang sepele, seolah-olah hanya interaksi basa-basi di jalanan. Namun, di balik itu, catcalling menyimpan persoalan serius tentang seksisme, kuasa, dan ruang publik yang tidak aman bagi sebagian orang—terutama perempuan.
Apa Itu Catcalling?
Secara sederhana, catcalling adalah tindakan pelecehan verbal di ruang publik, biasanya berupa komentar seksual, siulan, atau panggilan bernada menggoda yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuan mereka.
Istilah “catcall” sendiri berasal dari abad ke-17 di Inggris, merujuk pada bunyi siulan yang ditujukan untuk mengejek pertunjukan teater. Namun dalam konteks modern, ia berkembang menjadi istilah untuk menggambarkan pelecehan verbal di jalanan.
Catcalling bisa berupa:
- Siulan (whistling) atau suara menggoda.
- Panggilan bernada seksual: “Hai seksi,” “manis banget,” atau sejenisnya.
- Pertanyaan atau komentar yang bernuansa tubuh: “Badannya oke banget,” atau “Mau ditemenin, sayang?”
- Gerakan tubuh atau ekspresi wajah yang melecehkan.
Ciri khas catcalling adalah: tidak diminta, bernuansa seksual, dan membuat targetnya tidak nyaman.
Catcalling Bukan Sekadar “Godaan Biasa”
Bagi sebagian orang—terutama pelaku—catcalling sering dianggap bentuk pujian. Mereka berkata, “Loh, salahnya apa sih dipuji cantik?” atau “Kita kan cuma bercanda.”
Namun, yang luput dari pemahaman itu adalah posisi kuasa. Catcalling bukanlah komunikasi setara antara dua individu. Ia terjadi secara sepihak, tanpa persetujuan, dan sering menempatkan korban dalam posisi rentan.
Bayangkan: seorang perempuan berjalan sendirian, lalu sekelompok laki-laki meneriakkan komentar bernuansa seksual. Dalam kondisi itu, sulit bagi korban untuk merasa aman. Apakah ia harus membalas? Mengabaikan? Atau mempercepat langkah sambil menahan rasa cemas?
Catcalling, dalam hal ini, bukan soal “rayuan” tetapi soal intimidasi. Ia menjadikan jalanan bukan lagi ruang publik netral, melainkan arena di mana tubuh seseorang dijadikan konsumsi bebas.
Mengapa Catcalling Terjadi?
Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang membuat catcalling tetap hidup dan seakan “normal” dalam masyarakat:
1. Budaya Patriarki
Di banyak masyarakat, termasuk Indonesia, masih kuat anggapan bahwa laki-laki punya kuasa lebih atas ruang publik. Catcalling menjadi salah satu ekspresi kuasa itu—menggunakan tubuh orang lain sebagai bahan komentar tanpa izin.
2. Normalisasi Sosial
Banyak orang menganggap catcalling “lumrah.” Bahkan ada pepatah populer: “Kalau cantik wajar digodain.” Pola pikir ini membuat pelecehan dianggap hal biasa, bahkan sampai diinternalisasi oleh sebagian korban.
3. Kurangnya Kesadaran Hukum
Di Indonesia, pelecehan seksual verbal sering kali tidak dianggap serius. Padahal, menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS 12/2022), pelecehan seksual verbal termasuk tindak pidana.
4. Tekanan Maskulinitas Toksik
Ada pandangan bahwa menjadi “laki-laki sejati” harus berani menggoda perempuan di jalan. Catcalling dipakai sebagai ajang pembuktian maskulinitas, meskipun sebenarnya itu bentuk agresi verbal.
Dampak Catcalling bagi Korban
Meski bagi pelaku terasa ringan, dampaknya bagi korban bisa cukup serius:
- Rasa Tidak Aman
Banyak perempuan mengaku lebih waspada saat berjalan sendirian. Mereka memilih jalur memutar, memakai pakaian tertentu, atau berpura-pura menelepon demi menghindari perhatian. - Trauma Psikologis
Catcalling dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, bahkan trauma berkepanjangan. Riset di berbagai negara menunjukkan pelecehan di jalan bisa berkontribusi pada gangguan kecemasan sosial. - Pembatasan Mobilitas
Akibat rasa tidak aman, korban cenderung membatasi diri. Ruang publik yang seharusnya bisa diakses bebas malah menjadi tempat yang penuh perhitungan. - Normalisasi Kekerasan Seksual
Catcalling sering jadi pintu masuk. Jika dibiarkan, ia bisa berlanjut pada bentuk pelecehan yang lebih serius.
Catcalling di Indonesia: Sebuah Cermin Sosial
Di kota-kota besar Indonesia, catcalling sudah menjadi “pemandangan umum.” Di halte bus, trotoar, kampus, bahkan kompleks perumahan.
Sebuah survei Hollaback! Jakarta (2016) bekerja sama dengan Cornell University menemukan bahwa 99% perempuan di Jakarta pernah mengalami pelecehan di ruang publik, termasuk catcalling. Angka ini mencengangkan: artinya hampir semua perempuan pernah menjadi korban.
Namun, perlawanan mulai tumbuh. Kampanye seperti “Bye Catcall” dan gerakan media sosial dengan tagar #StopStreetHarassment menyoroti isu ini, mendorong masyarakat untuk melihat catcalling bukan sebagai candaan, tetapi pelecehan.
UU TPKS yang baru disahkan pada 2022 juga menjadi payung hukum. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pelecehan seksual non-fisik (termasuk verbal) bisa dipidana. Meski begitu, implementasi dan kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan besar.
Apakah Catcalling Sama dengan Flirting?
Banyak yang mencoba menyamakan catcalling dengan flirting (menggoda). Padahal keduanya sangat berbeda.
Flirting: dilakukan dengan persetujuan, biasanya dalam interaksi dua arah, dengan konteks saling tertarik.
Catcalling: sepihak, tanpa izin, bernuansa merendahkan, dan sering membuat target tidak nyaman.
Perbedaan mendasarnya adalah consent (persetujuan). Tanpa itu, semua komentar bernada seksual bisa jatuh menjadi pelecehan.
Bagaimana Mengatasi Catcalling?
Mengatasi catcalling bukan hanya urusan korban, tapi tanggung jawab bersama. Beberapa langkah yang bisa dilakukan:
1. Kesadaran Kolektif
Masyarakat perlu mengubah pola pikir: catcalling bukan pujian. Media, sekolah, dan komunitas bisa berperan dalam edukasi.
2. Dukungan pada Korban
Jangan menyalahkan korban dengan komentar seperti “mungkin bajunya terlalu terbuka.” Pelecehan selalu kesalahan pelaku, bukan korban.
3. Intervensi Aman (Bystander Intervention)
Jika melihat catcalling, orang sekitar bisa memberi dukungan pada korban—misalnya dengan hadir di sampingnya atau mengalihkan perhatian.
4. Hukum yang Tegas
Implementasi UU TPKS harus diperkuat, termasuk mekanisme pelaporan yang mudah dan aman.
5. Refleksi Individu
Bagi laki-laki, penting bertanya pada diri sendiri: “Apakah komentar ini akan membuat orang lain nyaman?” Jika tidak, sebaiknya diam.
Jalan Panjang Menuju Ruang Publik yang Aman
Catcalling adalah pintu kecil yang membuka pada diskusi lebih luas tentang siapa yang merasa aman di ruang publik, dan siapa yang tidak. Selama pelecehan verbal masih dianggap lumrah, maka ruang publik tidak akan pernah netral.
Perlu ada kesadaran bahwa jalan raya, trotoar, halte, atau taman bukan panggung hiburan bagi ego seksual seseorang. Mereka adalah ruang bersama, tempat semua orang berhak merasa aman tanpa harus dihantui siulan atau komentar yang merendahkan.
Penutup
Catcalling mungkin tampak ringan bagi sebagian orang, tapi ia adalah bentuk pelecehan yang nyata. Ia mencerminkan ketidaksetaraan, membatasi kebebasan bergerak, dan menciptakan rasa tidak aman.
Menghentikan catcalling bukan sekadar menutup mulut, tapi juga membuka kesadaran. Bahwa setiap tubuh adalah milik individu, bukan milik publik. Bahwa jalanan seharusnya bukan arena pelecehan, tapi ruang hidup yang setara.
Seperti kata sebuah slogan kampanye internasional:
“My dress is not a yes, my walk is not an invitation, and my smile is not consent.”
Catcalling bukan pujian. Ia pelecehan, dan sudah saatnya kita berhenti menganggapnya sepele.