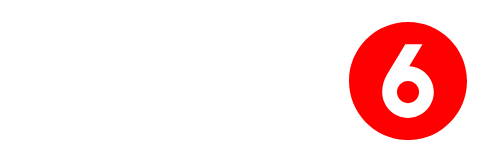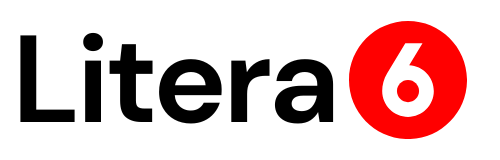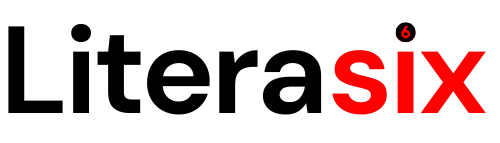Di era digital, kita hidup dalam arus informasi yang tidak pernah berhenti. Setiap hari, layar ponsel dipenuhi notifikasi: ada teman yang baru saja berlibur, selebriti favorit merilis produk terbaru, atau e-commerce mengingatkan tentang promo yang “hanya berlaku hari ini”.
Semua hal itu menciptakan rasa seakan kita harus selalu hadir, selalu tahu, dan selalu ikut serta. Perasaan cemas ketika tidak mengikuti tren, tidak membeli produk yang sedang populer, atau tidak hadir dalam sebuah momen sosial kini menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah FOMO—Fear of Missing Out.
Apa Itu FOMO?
FOMO atau Fear of Missing Out adalah istilah yang menggambarkan kecemasan seseorang ketika merasa tertinggal dari suatu momen, tren, atau informasi penting. Istilah ini mulai populer di awal 2000-an, namun menemukan puncaknya di era media sosial saat ini.
Rasa takut ketinggalan tersebut muncul bukan hanya pada hal-hal besar, seperti kabar politik atau peluang karier, tetapi juga pada hal-hal sederhana seperti tidak ikut liburan, tidak mencoba makanan baru yang sedang viral, hingga tidak memiliki gadget keluaran terbaru. Menurut Global Web Index (2023), lebih dari 56% pengguna internet global mengaku pernah merasa cemas karena tidak mengikuti tren atau informasi terkini.
Angka ini menunjukkan bahwa FOMO sudah menjadi fenomena global yang melekat dalam keseharian masyarakat modern.
Bagaimana FOMO Bekerja?
FOMO bekerja dengan memanfaatkan kebutuhan dasar manusia: ingin diterima secara sosial, ingin diakui, dan ingin memiliki pengalaman baru. Media sosial menjadi katalis utama dalam memperkuat dorongan ini.
Ketika seseorang melihat unggahan liburan temannya, pencapaian karier orang lain, atau gaya hidup mewah selebriti, otak secara alami membandingkan kondisi diri dengan apa yang dilihat. Perbandingan tersebut memicu rasa cemas, seolah hidup sendiri tidak cukup baik jika tidak melakukan hal yang sama.
Psikolog Andrew Przybylski dari University of Oxford menyebutkan bahwa FOMO erat kaitannya dengan kebutuhan akan keterhubungan sosial. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, individu merasa tertinggal, kurang berharga, dan terdorong untuk melakukan sesuatu agar tetap relevan.
Dampak FOMO Terhadap Kehidupan Sehari-hari
Fenomena FOMO berdampak luas pada kesehatan mental, kondisi finansial, hingga hubungan sosial. Dari sisi kesehatan mental, FOMO dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kecemasan, stres, bahkan depresi.
Studi Journal of Social and Clinical Psychology (2018) menemukan bahwa individu dengan tingkat FOMO tinggi cenderung merasa tidak puas dengan hidupnya. Dari sisi finansial, FOMO mendorong perilaku konsumtif, seperti membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti flash sale hanya karena takut kehabisan, atau berinvestasi di produk keuangan yang tidak dipahami.
Sementara itu, dalam hubungan sosial, FOMO sering menimbulkan rasa iri, perbandingan berlebihan, dan kecenderungan untuk lebih fokus pada pencitraan digital daripada interaksi nyata.
FOMO dalam Dunia Digital dan Industri
Di era digital, FOMO tidak hanya muncul secara alami, tetapi juga sengaja dirancang oleh industri. Perusahaan teknologi dan e-commerce memanfaatkan rasa takut ketinggalan untuk mendorong konsumsi.
Notifikasi media sosial dirancang agar pengguna terus merasa ada sesuatu yang penting untuk dilihat. E-commerce menambahkan label “hanya tersisa 1 barang” atau “promo berakhir 2 jam lagi” untuk menciptakan urgensi. Industri hiburan juga memainkan peran besar dengan menciptakan tren eksklusif, seperti tiket konser yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas.
Semua strategi ini pada dasarnya membangun ekosistem yang mengandalkan FOMO sebagai bahan bakar utama, membuat orang selalu terjebak dalam siklus konsumsi dan keterhubungan digital tanpa henti.
Bagaimana Mengatasi FOMO?
Meski sulit dihindari, FOMO dapat dikelola dengan kesadaran dan strategi tertentu. Salah satunya adalah membatasi waktu penggunaan media sosial.
Penelitian menunjukkan bahwa mengurangi durasi media sosial hingga 30 menit per hari dapat menurunkan rasa cemas dan meningkatkan kepuasan hidup. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran diri bahwa apa yang tampil di media sosial seringkali hanya versi terbaik dari kehidupan orang lain, bukan realitas sepenuhnya. Membuat prioritas pribadi juga menjadi langkah penting: tanyakan pada diri sendiri apakah suatu aktivitas benar-benar bermanfaat, atau sekadar dorongan untuk mengikuti tren.
Konsep JOMO (Joy of Missing Out) juga bisa menjadi alternatif, yaitu seni menikmati ketenangan dengan tidak ikut serta dalam semua hal, dan merayakan kebahagiaan dalam aktivitas sederhana tanpa perlu validasi digital.
Refleksi Akhir
FOMO adalah fenomena yang lahir dari kebutuhan manusia untuk terhubung, tetapi dalam perkembangannya diperkuat oleh industri digital dan pola konsumsi modern. Jika tidak dikelola dengan bijak, FOMO dapat mengikis kesehatan mental, mengganggu stabilitas finansial, dan melemahkan hubungan sosial.
Namun, dengan membangun kesadaran, menetapkan prioritas, dan melatih diri untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, kita bisa mengubah FOMO menjadi JOMO—sebuah cara pandang yang lebih sehat terhadap hidup. Pada akhirnya, pertanyaannya adalah: apakah kita benar-benar mengendalikan pilihan hidup kita, ataukah kita hanya mengikuti arus tren yang dibentuk oleh algoritma dan industri?
Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah kita hidup dengan tenang, atau terus-menerus dikejar oleh rasa takut ketinggalan.