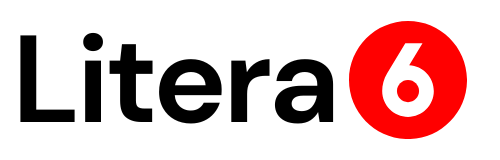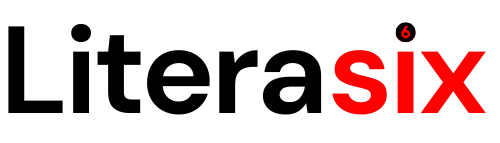OpenAI bersiap melepas mahluk cerdas generasi kelimanya ke dunia: GPT‑5. Tak seperti rilis sebelumnya yang membawa euforia global, peluncuran kali ini justru menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam—bukan sekadar “apa yang bisa dilakukan model ini?”, melainkan: untuk siapa kecerdasan ini sebenarnya dibangun?
Mereka yang lebih dahulu mengujinya mengaku terkesima. GPT‑5, katanya, mahir menulis kode, menyelesaikan persoalan logika, bahkan menunjukkan kemampuan reasoning lebih tajam dari sebelumnya. Tapi sebagian lainnya berbisik—lompatan dari GPT‑4 ke GPT‑5 tidak sedrastis dari GPT‑3 ke GPT‑4.
Namun lompatan yang paling nyata justru terjadi di sisi valuasi:
OpenAI kini mengincar $500 miliar, angka yang didorong bukan oleh misi kemanusiaan, tetapi oleh kemungkinan karyawan menjual sahamnya. Target pendapatan tahunan? $20 miliar sebelum 2025 berakhir.
Apa yang sedang dijual di sini? Algoritma? Harapan? Atau sekadar akses tak terbatas ke pola-pola prediksi yang kita sebut “kecerdasan”?
Di Balik Neural Network, Ada Aliran Listrik
GPT‑5 adalah hybrid. Bukan hanya sekadar model besar yang dilatih di atas triliunan token, ia juga menggabungkan teknik seperti test-time compute—sebuah sistem di mana otak buatan ini bisa “berpikir lebih dalam” saat digunakan.
Namun otak tak bisa berjalan tanpa tubuh. Dan tubuh AI bukan silikon semata. Ia memerlukan daya listrik dalam jumlah yang kian tak wajar.
Laporan dari earnings season menunjukkan satu hal:
“AI boom telah mengerek tagihan listrik global.”
Dan di sinilah ironi teknologi bertemu realitas planet: demi menjalankan satu kueri AI, server harus menelan daya setara berjam-jam pendingin ruangan, atau ratusan liter air pendingin. Sementara itu, Google dan para raksasa cloud mulai membatasi penggunaan daya mereka agar jaringan listrik tidak jebol. Pertanyaannya: apakah mereka benar-benar menyesal, atau hanya sedang merapikan citra?
Di Antara Manusia dan Mesin, Siapa yang Sedang Dijinakkan?
Mari kita jujur—teknologi tidak pernah benar-benar netral. Ia lahir dari sistem yang sudah lama tidak netral: ekonomi yang bertumpu pada keuntungan, bukan keberlanjutan; pada pertumbuhan tak terbatas, bukan keseimbangan sosial. Kecerdasan buatan hanyalah kelanjutan dari cerita lama: produksi, efisiensi, dan kontrol.
Dalam skala mikro, GPT‑5 bisa menulis puisi, menyusun ulang rencana bisnis, hingga membuat analisis pasar dalam hitungan detik. Namun dalam skala makro, ia adalah mesin yang dibangun untuk memperkuat posisi perusahaan yang sudah sangat kuat. Dilansir dari Reuters, OpenAI tengah dalam pembicaraan untuk memungkinkan karyawan menjual saham dengan valuasi mencapai $500 miliar—angka yang nyaris dua kali lipat dari beberapa bulan sebelumnya.
Kapitalisme, seperti biasa, tahu bagaimana mengepak ilusi dan menjualnya sebagai masa depan.
GPT‑5 bukan hanya soal kemampuan teknis. Ia adalah alat negosiasi dalam ruang boardroom, amunisi baru dalam persaingan antar raksasa cloud, dan simbol baru supremasi teknologi dalam imajinasi publik.
Infrastruktur yang Tak Pernah Netral
Ketika kita memuji kecanggihan AI, kita jarang membicarakan infrastruktur yang menopangnya. Data center tidak melayang di awan; mereka menjejak keras di tanah, memakan energi, air, dan lahan.
Pada musim panas 2024, seperti dilansir Reuters dalam laporan earnings season, lonjakan penggunaan daya oleh perusahaan AI menyebabkan kenaikan signifikan pada tagihan listrik global. Di Amerika Serikat, beberapa wilayah bahkan terpaksa menyesuaikan strategi distribusi listrik demi menghindari blackout akibat beban dari server-server AI.
Ironisnya, teknologi yang diharapkan membantu mengatasi krisis iklim justru memperparahnya lewat jejak karbon yang makin membesar. Ini bukan lagi spekulasi. Ini sudah menjadi pola.
Ketika satu permintaan AI memerlukan ratusan liter air pendingin dan sejumlah energi setara beberapa rumah tangga dalam sehari, kita perlu bertanya: di mana batas antara inovasi dan kerakusan?
Dari Demokratisasi ke Dominasi
Saat AI pertama kali muncul dalam wacana publik, kita dijanjikan demokratisasi teknologi. Kita dibujuk untuk percaya bahwa siapa saja, dari petani di pelosok hingga peneliti di kampus, akan mendapat akses yang setara.
Tapi realitasnya tak seindah itu.
Model-model seperti GPT‑5 mungkin akan “terbuka”—tapi hanya sejauh yang diizinkan oleh perusahaan pemiliknya. Open-weight bukan berarti open-access. Dan akses bukan berarti kontrol. Kita hanya diberi ilusi partisipasi dalam ekosistem yang sudah dikendalikan oleh mereka yang punya modal dan komputasi.
Dalam pernyataan internal, CEO OpenAI menyebut GPT‑5 sebagai lompatan menuju “AI yang mampu bernalar lebih dalam dan bertindak lebih efektif.” Tapi pertanyaannya tetap: bertindak untuk siapa?
Untuk perusahaan yang ingin merampingkan tenaga kerja? Untuk algoritma iklan yang lebih presisi? Atau untuk masyarakat yang berharap AI bisa menyembuhkan kanker, mengajar anak-anak di pelosok, atau membantu meredam krisis lingkungan?
Jawaban itu belum kita lihat. Dan mungkin, memang bukan kita yang akan menentukan.
Dunia Tiga Kecepatan
Kita tengah menyaksikan munculnya dunia dengan tiga kecepatan:
- Negara-negara maju yang membangun dan mengendalikan AI;
- Negara berkembang yang hanya bisa menjadi konsumen dan pengguna;
- Komunitas rentan yang bahkan belum punya listrik stabil untuk mengakses AI.
Kesenjangan ini bukan kesalahan teknis, tapi konsekuensi politis dari bagaimana teknologi dibangun dan didistribusikan.
Palantir, Nvidia, dan Alphabet—seperti dilaporkan Reuters—terus mengucurkan investasi ke perusahaan-perusahaan AI, bahkan ke startup yang belum memiliki produk komersial, tetapi menjanjikan “masa depan”. Sementara itu, di banyak wilayah di dunia, sekolah-sekolah masih kekurangan buku, bukan model bahasa.
Pertanyaannya kini bukan hanya soal “seberapa pintar GPT‑5?”, tetapi “mengapa kecerdasan selalu terkonsentrasi di tempat yang sama?”
AI Sebagai Simbol: Mimpi atau Monster?
Seperti atom di awal abad ke-20, AI kini menjadi simbol ambivalen: kemajuan dan kehancuran.
Di satu sisi, ia menjanjikan dunia baru—lebih efisien, lebih cerdas, lebih terkoneksi. Tapi di sisi lain, ia memantik kecemasan eksistensial yang tidak kalah nyata: kehilangan kendali, hilangnya makna kerja, dan lunturnya relasi antar manusia.
Kita mungkin tidak akan mengalami skenario Terminator, tapi kita sudah mulai melihat bagaimana keputusan-keputusan penting—penerimaan kerja, kredit bank, bahkan vonis hukum—mulai dialihkan ke mesin. Dan seperti semua sistem buatan manusia, mesin juga bisa bias. Atau lebih buruk: dirancang memang untuk bias.
GPT‑5 adalah alat. Tapi alat selalu mencerminkan niat pembuatnya.
Mendorong Ruang Kritik, Bukan Hanya Konsumsi
Literasix tidak hadir untuk menjual optimisme kosong. Kami hadir untuk menulis ulang narasi yang terlalu sering didikte oleh industri dan media arus utama. Kami percaya, kritik bukan hambatan, tapi prasyarat kemajuan yang beradab.
Karena itu kami akan terus bertanya:
- Mengapa valuasi lebih penting dari transparansi?
- Mengapa energi bisa dibakar demi latency milidetik?
- Mengapa kita lebih cepat mengembangkan AI yang bisa menggambar wajah, ketimbang AI yang bisa memahami penderitaan?
AI mungkin akan terus berkembang. Tapi apakah kita sebagai manusia juga ikut berkembang dalam menyikapinya?
Penutup: Di Antara Kabel dan Kesadaran
GPT‑5, pada akhirnya, adalah cermin. Ia memantulkan kembali nilai-nilai yang kita tanamkan ke dalamnya. Dan seperti semua cermin, ia bisa menipu jika kita tak cukup jujur melihat ke dalam.
Apakah kita akan terus menyuntikkan miliaran dolar ke dalam model yang semakin pintar, namun semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan?
Ataukah kita mulai membangun alternatif—AI yang bukan hanya cerdas secara komputasional, tapi juga bijak secara sosial?
Literasix percaya, masa depan tak akan dibentuk oleh parameter token per second, tapi oleh keberanian kita memilih jalan yang tak selalu efisien, tapi lebih adil.