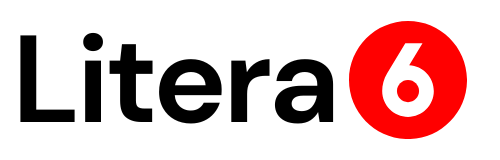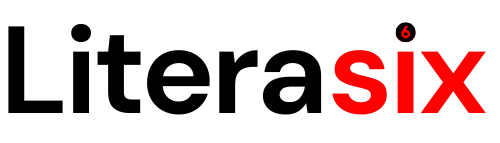Stoisisme lahir di Athena pada awal abad ke-3 SM, ketika seorang pedagang asal Siprus bernama Zeno dari Citium memutuskan untuk menekuni filsafat setelah kapal dagangnya karam. Ia kemudian mengajar di serambi berpilar (Stoa Poikile), dan dari situlah nama Stoisisme berasal.
Berbeda dari filsafat yang hanya berkutat di ruang diskusi, Stoisisme sejak awal ditujukan untuk praktik hidup. Ia mengajarkan manusia untuk menemukan ketenangan, bukan dengan mengendalikan dunia, tetapi dengan mengendalikan diri.
Di tengah keramaian Athena, Stoisisme memberi pelajaran sederhana: penderitaan sering kali lahir bukan dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadap kenyataan. Inilah sebabnya Stoisisme terasa relevan, baik bagi prajurit Romawi dua ribu tahun lalu maupun bagi karyawan yang terjebak macet di jalan raya hari ini.
Hidup Sesuai Alam: Inti Pemikiran Stoik
Jika harus dirangkum dalam satu kalimat, inti ajaran Stoisisme adalah: hidup sesuai dengan alam. Namun, “alam” di sini bukan sekadar pepohonan, sungai, dan gunung, melainkan tatanan rasional yang mengatur semesta.
Stoik percaya pada konsep logos—akal universal yang menata segalanya. Manusia, sebagai makhluk berakal, adalah bagian dari logos. Karena itu, tugas utama manusia adalah selaras dengan tatanan kosmos ini, bukan melawan arusnya.
Prinsip dasar mereka sederhana tapi mendalam:
-
Satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan (virtue).
-
Kekayaan, jabatan, kesehatan, atau bahkan umur panjang bukanlah kebaikan sejati, melainkan “indifferents”—hal-hal yang boleh ada, tapi tidak menentukan kebahagiaan.
-
Sebaliknya, penderitaan, kemiskinan, atau penyakit bukanlah kejahatan mutlak, karena kebahagiaan sejati terletak pada sikap batin, bukan kondisi luar.
Dengan demikian, Stoisisme mengajarkan semacam kebebasan batin: tidak ada yang benar-benar bisa merenggut ketenangan dari diri seseorang, kecuali jika orang itu sendiri menyerahkannya.
Contoh klasiknya adalah dichotomy of control—pemahaman bahwa sebagian hal dalam hidup berada di bawah kendali kita, sebagian lagi tidak. Sikap Stoik adalah fokus pada yang bisa kita kendalikan (pikiran, sikap, keputusan), dan menerima dengan lapang dada yang tidak bisa kita kendalikan (cuaca, kematian, opini orang lain).
Dengan prinsip ini, Stoisisme tidak menjanjikan kebahagiaan berupa ekstasi atau euforia, melainkan ketenangan mendalam (ataraxia).
Antara Kebahagiaan dan Penderitaan: Bagaimana Stoik Menghadapinya
Di mata kaum Stoik, kehidupan manusia penuh pasang surut: lahir dan mati, sakit dan sehat, pujian dan hinaan, untung dan rugi. Semua itu seperti ombak yang datang silih berganti. Namun, Stoisisme mengajarkan bahwa kita bisa tetap tenang, bahkan ketika badai terbesar menghantam.
Stoik menganggap emosi negatif seperti marah, takut, iri, atau putus asa muncul karena kita melekat pada hal-hal yang sebetulnya di luar kendali. Jika kita belajar melihat dunia dengan jernih, emosi itu tidak akan menguasai kita.
Misalnya, kehilangan harta. Bagi orang biasa, ini bisa berarti bencana. Namun, bagi Stoik, harta hanyalah sesuatu yang “indifferent”. Jika ada, gunakanlah dengan bijak. Jika hilang, terimalah dengan tenang. Yang lebih penting adalah bagaimana sikap kita terhadap peristiwa itu.
Begitu juga dengan penderitaan. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya budak, berkata: “Bukan peristiwa yang menyiksa manusia, melainkan cara mereka menilainya.” Artinya, penderitaan fisik mungkin tak terhindarkan, tapi penderitaan batin sering lahir dari interpretasi kita sendiri.
Stoisisme bukan berarti mematikan emosi, melainkan mengatur hubungan kita dengan emosi. Seorang Stoik boleh bersedih, tapi tidak dikuasai kesedihan. Ia boleh marah, tapi tidak larut dalam kemarahan. Bagi mereka, kebebasan sejati adalah kebebasan dari perbudakan emosi.
Inilah mengapa Stoisisme sering digambarkan sebagai filsafat ketangguhan mental. Ia bukan sekadar teori, tapi seni menjalani hidup dengan tenang meski dunia tidak pernah tenang.
Stoisisme dan Kekaisaran Romawi
Stoisisme menemukan rumah barunya di Roma, di mana ia berkembang bukan hanya sebagai filsafat pribadi, tetapi juga sebagai pedoman moral politik.
Tokoh-tokoh besar Romawi menjadi penganut Stoik. Seneca, penasihat Kaisar Nero, menulis surat-surat filsafat yang penuh refleksi tentang waktu, kematian, dan ketenangan batin. Meski hidup di istana penuh intrik, ia berusaha menerapkan prinsip Stoik dalam politik yang kejam.
Ada pula Epictetus, mantan budak yang kemudian menjadi guru filsafat. Dari status sosial rendah, ia naik menjadi salah satu filsuf paling dihormati di zamannya. Ajarannya menekankan bahwa siapa pun, bahkan budak sekalipun, bisa meraih kebebasan sejati melalui kendali diri.
Dan tentu saja, ada Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf, yang meninggalkan catatan pribadinya dalam Meditations. Buku itu bukan ditulis untuk publik, melainkan sebagai renungan pribadi di tengah kesibukan memimpin perang. Di dalamnya, kita melihat seorang penguasa dunia yang tetap berusaha hidup sederhana, rendah hati, dan selaras dengan alam.
Bagi bangsa Romawi yang menjunjung disiplin, keteguhan, dan pengendalian diri, Stoisisme terasa sangat cocok. Ia menjadi filsafat resmi tidak tertulis dari kekaisaran—panduan bagi tentara, negarawan, bahkan warga biasa.
Dari Zeno ke Kaisar: Para Tokoh Stoisisme
Stoisisme memiliki perjalanan panjang, dari Yunani ke Romawi.
-
Zeno dari Citium – pendiri, yang menekankan hidup sesuai dengan alam.
-
Chrysippus – perumus sistem logika Stoik, menjadikan Stoisisme lebih kokoh.
-
Seneca – filsuf Romawi sekaligus penasihat istana, menulis esai tentang bagaimana tetap tenang di tengah kekuasaan.
-
Epictetus – mantan budak yang mengajarkan bahwa manusia bisa merdeka melalui pikirannya, meskipun tubuhnya terbelenggu.
-
Marcus Aurelius – kaisar Romawi sekaligus filsuf, menulis Meditations, catatan pribadi tentang bagaimana menjadi bijak di tengah beban memimpin sebuah imperium.
Dari budak hingga kaisar, Stoisisme membuktikan diri sebagai filsafat universal. Ia bisa diterapkan oleh siapa saja, di mana saja, tanpa memandang status.
Stoisisme dalam Kritik dan Perdebatan
Meski Stoisisme dihormati, bukan berarti ia tanpa kritik.
Kaum Epikurean menuduh Stoik terlalu keras menolak kesenangan, seolah-olah hidup harus dijalani dengan wajah kaku tanpa tawa. Sementara kaum Skeptis mempertanyakan: bagaimana kita bisa yakin bahwa kebajikan adalah kebaikan sejati, jika semua pengetahuan manusia selalu bisa diragukan?
Bahkan dalam sejarah modern, beberapa orang menilai Stoisisme terlalu “dingin”—terlalu menekankan logika, sehingga mengabaikan sisi emosional manusia. Apakah mungkin kita hidup sepenuhnya tanpa terikat pada cinta, keluarga, atau ambisi?
Namun, justru dalam kritik itulah Stoisisme tetap relevan. Ia bukan jawaban mutlak, melainkan undangan untuk merefleksikan bagaimana kita menyikapi hidup. Stoisisme mengingatkan bahwa banyak penderitaan berasal dari diri kita sendiri—dari keinginan yang tak terkendali, dari ambisi yang tak pernah puas, dari takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya fana.
Jejak Stoisisme dalam Kehidupan Modern
Dua ribu tahun berlalu, tapi Stoisisme tetap hidup, bahkan semakin populer.
Dalam psikologi modern, prinsip Stoik tentang kendali diri dan interpretasi terhadap peristiwa menjadi dasar bagi Cognitive Behavioral Therapy (CBT)—salah satu metode terapi paling efektif untuk mengatasi kecemasan dan depresi.
Dalam dunia bisnis dan kepemimpinan, Stoisisme dipelajari sebagai strategi menghadapi tekanan. Banyak tokoh, dari pemimpin perusahaan hingga atlet profesional, mengutip Marcus Aurelius atau Seneca untuk menjaga fokus dan ketenangan.
Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, Stoisisme menjadi pegangan. Di era media sosial, di mana opini orang lain bisa dengan cepat menjatuhkan mental, Stoisisme mengingatkan: yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita, bukan komentar orang lain.
Bukan kebetulan jika dalam situasi krisis global—pandemi, perubahan iklim, ketidakpastian politik—Stoisisme kembali diminati. Ia menawarkan sesuatu yang langka di dunia modern: ketenangan batin yang tidak tergantung pada dunia luar.
Stoisisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa memilih takdir, tapi kita bisa memilih sikap. Dan dalam pilihan itulah, kebebasan sejati ditemukan.